Saya Seorang Rasis
Cina dan Pribumi. Dua ras yang telah lama sama-sama menghuni negara Indonesia. Saya sendiri adalah seorang Cina. Untuk menceritakan sebuah tulisan dengan judul yang kontroversial seperti ini, rasanya lebih baik kalau saya memulainya dari awal, supaya jelas duduk perkaranya.
Seperti pernah saya ceritakan sebelumnya, lima tahun terakhir ini saya menderita sebuah penyakit langka yang disebut Dystonia. Akibat dari penyakit ini, leher saya sering bergerak-gerak sendiri. Gejala tersebut tentunya cukup tak lazim dan tentunya akan mengundang perhatian banyak orang jika penderitanya berada di tempat umum, paling tidak begitulah yang saya alami. Diperhatikan oleh banyak orang tentunya merupakan hal yang membanggakan, tapi itu hanya berlaku kalau penyebab anda diperhatikan adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif dan aneh seperti Dystonia ini.
Gejala tersebut sudah cukup untuk membuat penderitanya (termasuk saya) mengalami stres yang berkepanjangan, apalagi mengingat penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya. Coba saja anda gerak-gerakkan leher anda terus-menerus selama satu jam saja, rasanya tidak aneh kalau anda segera berkunjung ke Rumah Sakit terdekat. Tapi bukan gejala itu yang ada hubungannya dengan judul artikel ini, melainkan gejala lainnya lagi.
Penyakit ini tidak hanya mempengaruhi otot leher saya, tapi juga otot muka saya. Akibatnya, muka saya acap kali terlihat melotot dan seperti orang yang ngajak ribut, padahal itu bukan karena saya memang sedang ingin mengajak ribut, tapi itu merupakan bagian dari penyakit ini. Mungkin juga muka saya memang sudah dari sananya seperti orang yang ngajak ribut, dan diperparah dengan penyakit ini. Saya tidak tahu. Yang jelas muka yang ngajak ribut ini memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan dan kewarasan saya.
Sejak menderita penyakit ini lima tahun yang lalu, menjadi bahan perhatian orang banyak saat berada di tempat umum sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Awalnya hal itu tentu membuat saya sangat tertekan, tetapi setelah sekian lama, ternyata saya masih saja tertekan. Uniknya, setelah lima tahun menjalani terapi yang rutin dan bertele-tele, penyakit saya mulai membaik, tapi sayangnya, walau gerakan kurang ajar dari leher saya sudah mulai berkurang, muka saya masih saja seperti orang ngajak ribut. Akibatnya, jika awalnya orang yang melihat saya mungkin akan berpikir, "Nih orang kok mukanya ngajak ribut yah, tapi lehernya juga gerak-gerak melulu, oh berarti nih orang lagi sakit atau ini orang memang dasarnya aneh atau ini orang gila." Tapi sekarang, setelah muka ngajak ribut saya tidak disertai dengan gerakan-gerakan leher yang aneh, orang yang melihatnya akan berpikir, "Nih orang kok mukanya ngajak ribut yah, berarti nih orang emang mau ngajak ribut nih, sikaaattt!!!"
Cibiran dari orang-orang di tempat umum yang awalnya adalah, "Aneh nih orang," atau "Stres nih orang," atau "Gila nih orang," lama-kelamaan berubah menjadi makian seperti "Apa lu!" Kadang makian yang keluar cukup kasar sehingga tidak bisa saya tulis di sini. Namun makian yang paling membekas adalah, "Dasar Cina lu!"
Karena saya tinggal di Indonesia, maka yang paling banyak melontarkan makian-makian itu adalah orang Pribumi. Mungkin kalau saya tinggal di Canada, yang memaki saya adalah orang Bule. Bahkan mungkin kalau saya tinggal di Singapore, yang memaki saya adalah sesama orang Cina. Tapi kenyataannya saya tinggal di Indonesia, dan setelah mengalami kejadian tersebut berulang-ulang dalam jangka waktu lama, hal itu tidak bisa tidak membekas di hati saya.
Beberapa bulan terakhir, saya menjadi paranoid dengan orang Pribumi. Bila melihat orang yang warna kulitnya hitam sedikit saja, bahkan dari jauh sekalipun, saya akan gemetaran, keringat dingin, kadang bahkan seperti mau pingsan. Rasa takut yang saya alami sangat hebat. Bahkan saat liburan ke Bali sekalipun, rasanya seperti masuk ke kandang singa. Pergi ke tempat umum yang awalnya masih bisa saya nikmati, sekarang menjadi sebuah mimpi buruk. Lama-kelamaan paranoid saya semakin bertambah parah. Saya bahkan menjadi takut terhadap sopir ataupun teman-teman Pribumi yang sudah lama saya kenal. Saya tidak berani keluar rumah walau hanya selangkah. Saya bahkan menjadi jarang ke gereja. Bila harus keluar rumah untuk membeli barang yang benar-benar saya butuhkan, saya harus ditemani oleh teman saya. Bahkan untuk sekedar mencukur rambut di salon langganan, saya harus ditemani oleh ibu saya.
Paranoid ini terus bertambah parah sampai akhirnya, bahkan saat saya sedang berada di dalam rumah sekalipun, saya merasa kalau orang-orang Pribumi yang lewat di depan rumah dan juga para tetangga ikut mengatai-ngatai saya, tanda patognomonik kalau paranoid ini sudah mulai memasuki tahap psikotik. Menyadari bahwa kondisi saya tidak kunjung membaik dan malah bertambah parah, saya akhirnya berkunjung ke psikiater dan seperti sudah saya duga, psikiater meresepkan saya obat anti psikotik. Berkunjung ke psikiater dan minum obat anti psikotik rasanya sudah cukup untuk menggambarkan tingkat keseriusan dari masalah yang saya hadapi. Tidak ada orang waras yang bersedia untuk minum obat dari psikiater kalau masalahnya masih bisa ia hadapi sendiri.
Yang membuat saya kecewa, sang psikiater tampaknya benar-benar hanya mengandalkan obat tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahan saya. Saya berharap sang psikiater akan memberikan Cognitive Behaviour Therapy, konseling, ataupun tips dan trik untuk saya mengatasi ketakutan ini. Gambaran yang ada di benak saya adalah saya berbaring di kursi panjang dan menceritakan semua keluh-kesah saya, sementara sang psikiater mendengarkan dan membuat catatan, seperti yang ditampilkan di film-film. Tapi ternyata tidak. Kenyataannya, kunjungan ke psikiater ini sama seperti ketika saya berobat ke dokter kulit untuk mengobati jerawat ataupun ke dokter umum untuk mengobati batuk pilek. Saya duduk, menceritakan gejala yang saya rasakan, dokter meresepkan obat, menyerahkan resep itu ke saya, dan saya pulang, dengan resep di tangan sebagai kunci jawaban untuk mengatasi semua gejala yang saya rasakan. Sang dokter tidak akan bertanya, "Apa perasaan anda terhadap gejala yang muncul di anda?" atau "Menurut anda, kenapa gejala itu bisa muncul?" atau "Menurut anda, bagaimana cara untuk mengatasi akar penyebab timbulnya gejala itu?"
Pada awalnya, obat ini memang sangat membantu saya. Gejala psikotik dan pikiran irasional mulai lenyap. Saya tidak lagi merasa orang yang lewat di depan rumah ataupun para tetangga mengatai saya tanpa alasan apapun. Akan tetapi saya tetap takut pada orang Pribumi. Bila bertemu mereka, saya merasa takut dan tidak nyaman. Seolah bagi saya, mereka adalah momok yang membenci kehadiran saya dan akan mengatai atau menyakiti saya. Saya sudah minum obat anti psikotik selama beberapa minggu, dan saya tidak merasa lagi ada kemajuan yang bisa diberikan obat ini. Saya tidak merasa kalau obat ini adalah jawaban untuk menghilangkan ketakutan saya. Di samping itu, tidak seperti obat jerawat ataupun obat flu, efek samping obat ini sangat berat dan malahan mengganggu produktivitas saya sehari-hari. Akhirnya saya putuskan untuk stop mengonsumsi obat ini dan juga tidak meneruskan kunjungan saya ke sang psikiater.
Lepas dari psikiater, saya mulai berkontemplasi untuk mencari jawaban atas permasalahan ini. Saya mulai merenung, kenapa saya harus takut dengan orang Pribumi? Kenapa saya harus memandang mereka sebagai momok yang begitu mengerikan? Saya kenal dengan banyak orang Pribumi dan mereka semua baik dan sopan terhadap saya, rasanya tidak adil kalau hanya karena perlakuan segelintir beberapa orang Pribumi terhadap saya, lantas saya memberikan stereotip dan prasangka buruk terhadap mereka semua. Tapi, seberapapun kerasnya logika dan hati nurani saya mencoba meyakinkan, kenyataannya saya tetap saja takut terhadap orang Pribumi. Saya bahkan acap kali bersembunyi bila ada tukang air, tukang listrik, ataupun petugas dari langganan internet yang datang ke rumah. Pernah suatu kali AC kamar saya rusak dan harus direparasi. Beberapa hari sebelum kedatangan sang tukang reparasi AC, saya tidak bisa tidur. Dan saat hari H tiba, hanya untuk menemani sang tukang reparasi AC yang sebenarnya juga adalah orang yang ramah, tingkat ketegangan yang saya rasakan seperti sedang terjun ke medan perang.
Saya amat terganggu dengan ketakutan ini, saya merasa kalau ketakutan ini tidak bisa saya atasi, hidup saya akan menjadi tidak maksimal dan tidak produktif. Saya melanjutkan perenungan saya, dan pada akhirnya, jawaban dari ketakutan saya hanya satu. Jawabannya sebenarnya amat sederhana, dan jawaban tersebut sama seperti judul artikel ini. Saya adalah seorang rasis. Ya, saya seorang rasis. Sekali lagi saya ucapkan supaya jadi pas tiga kali, saya adalah seorang rasis.
Setelah mengingat-ingat lagi dan melewati beberapa fase penyangkalan, saya akui bahwa sudah lama bibit-bibit rasisme ada dalam diri saya. Saya mungkin sebelumnya memiliki banyak teman Pribumi, tapi tetap saja saya selalu menjaga jarak dengan mereka. Tingkat persahabatan saya tidak akan sedalam dan seakrab dengan sesama orang Cina.
Agak susah untuk mengetahui kapan persisnya benih rasisme timbul dalam hati saya. Mungkin rasisme itu tertanam secara perlahan secara tidak sengaja oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk membenci Pribumi, tapi mereka selalu mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan orang Pribumi. Untuk memberikan orang tua saya sedikit pembelaan, mereka lahir pada tahun 60'-an. Mereka menghabiskan masa muda mereka pada masa Orde Baru. Di masa itu, kehidupan orang Cina tidaklah semudah pada masa sekarang, terutama setelah era Gus Dur. Orang Cina akan dipersulit bila harus mengurus surat-surat resmi ataupun izin usaha. Itulah kenapa banyak orang Cina yang mengganti nama mereka di akta lahir ataupun KTP menjadi lebih "ke-Pribumi-an", supaya ke-Cina-an mereka tidak terlalu kentara. Orang tua saya juga seringkali mengingatkan saya supaya jangan sampai berurusan dengan polisi ataupun aparat negara lainnya. Karena polisi akan lebih membela hak dan kepentingan orang Pribumi dibanding orang Cina, bahkan ketika orang Cina-lah yang menjadi korban dalam suatu perkara.
Dahulu saya selalu menganggap orang tua saya konyol, kalau ketakutan mereka itu berlebihan, dan kita juga sekarang telah hidup di era Milenium. Prasangka dan stereotip seperti itu sudah ketinggalan zaman. Tapi mungkin, seperti yang Sigmund Freud ajarkan, hal-hal negatif yang diceritakan orang tua saya itu tertanam kuat dalam alam bawah sadar atau Id saya, tanpa saya sadari. Selama ini saya berhasil mengontrol Ego atau alam sadar saya untuk mengingatkan bahwa beranggapan bahwa Pribumi itu jahat adalah hal yang tidak baik. Tapi setelah depresi yang berkepanjangan dan juga kejadian traumatis akhir-akhir ini, pertahanan Ego saya runtuh dan Id saya, yang penuh dengan insting primitif seperti ketakutan dan agresi, mengambil alih.
Pada akhirnya, saya menyadari bahwa untuk menghilangkan ketakutan ini, saya harus mengakui terlebih dahulu bahwa memang saya dasarnya adalah seorang rasis. Rasisme itulah yang membangun dinding pemisah antara saya, orang Cina, dengan orang Pribumi. Saat konsultasi dengan psikiater ataupun teman saya, saya acap kali membela diri dan mengatakan kalau saya tidak rasis, karena rasis itu membenci Pribumi, sementara saya takut dengan Pribumi. Tapi takut dan benci bagaikan dua sisi pada satu koin yang sama. Saya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menerima bahwa diri mereka memang rasis dan membenci golongan atau ras yang berbeda dengan mereka. Tidak ada orang yang senang membenci. Membenci itu melelahkan. Kebencian mereka juga berasal dari ketakutan, takut pada hal yang tidak mereka pahami. Ketakutan yang sama seperti saya.
Tujuan saya membuat tulisan ini, selain untuk terapi, adalah untuk membuat semacam pernyataan bahwa saya adalah seorang rasis, dan saya malu akan hal itu. Alam super-ego saya mengingatkan bahwa sifat rasisme saya ini adalah salah dan harus diperbaiki. Sifat ini hanya akan membawa kerugian dan malapetaka untuk saya sendiri. Orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan ataupun kebencian adalah orang yang membiarkan insting primitifnya mengontrol dirinya, dan akhirnya hidupnya akan semakin jauh dari ideal self-nya dan tidak akan mencapai potensi maksimal.
Saya memutuskan untuk berhenti menyalahkan paradigma Orde Baru yang sebenarnya juga bukan mengajarkan untuk membenci orang Cina, tapi untuk membenci ideologi komunisme. Sayangnya memang negara RRC saat itu merupakan salah satu kiblat komunisme terbesar di dunia, sehingga mungkin sampai sekarang orang Pribumi sudah terlanjur untuk mengasosiasikan orang Cina dengan komunisme dan segala mudarat yang disebabkan paham itu. Saya juga memutuskan untuk berhenti menyalahkan segelintir orang Pribumi yang mungkin pernah mengatai saya. Saya bahkan memutuskan untuk berhenti menyalahkan penyakit Dystonia saya. Hanya rasisme yang ada di hati saya sendiri inilah yang perlu dibenci dan diperbaiki.
Bila kebetulan anda yang membaca tulisan saya ini adalah seorang Pribumi, saya minta maaf kalau tulisan ini menyinggung perasaan anda, hal itu sama sekali bukan maksud saya. Tulisan ini saya maksudkan sebagai permintaan maaf atas kerasisan saya, dan lebih dari itu, juga merupakan permintaan tolong. Bila anda seorang Pribumi, saya harap anda tetap sudi untuk berteman dengan saya. Tolonglah ubah prasangka negatif saya ini dan bantulah saya untuk keluar dari belenggu paranoid, ketakutan, dan rasisme ini. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan rasisme, hanya kehangatan, keterbukaan hati, dan toleransi terhadap perbedaanlah yang dapat melakukannya.
Saya selalu bermimpi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, tapi bagaimana mungkin hal itu bisa saya lakukan kalau saya bahkan tidak bisa berdamai dengan tetangga saya sendiri. Seperti yang Michael Jackson pernah ucapkan, jika anda ingin menciptakan dunia yang lebih baik, mulailah dari sosok yang ada di dalam cermin.
Seperti pernah saya ceritakan sebelumnya, lima tahun terakhir ini saya menderita sebuah penyakit langka yang disebut Dystonia. Akibat dari penyakit ini, leher saya sering bergerak-gerak sendiri. Gejala tersebut tentunya cukup tak lazim dan tentunya akan mengundang perhatian banyak orang jika penderitanya berada di tempat umum, paling tidak begitulah yang saya alami. Diperhatikan oleh banyak orang tentunya merupakan hal yang membanggakan, tapi itu hanya berlaku kalau penyebab anda diperhatikan adalah hal yang positif, bukan hal yang negatif dan aneh seperti Dystonia ini.
Gejala tersebut sudah cukup untuk membuat penderitanya (termasuk saya) mengalami stres yang berkepanjangan, apalagi mengingat penyakit ini sampai sekarang belum ada obatnya. Coba saja anda gerak-gerakkan leher anda terus-menerus selama satu jam saja, rasanya tidak aneh kalau anda segera berkunjung ke Rumah Sakit terdekat. Tapi bukan gejala itu yang ada hubungannya dengan judul artikel ini, melainkan gejala lainnya lagi.
Penyakit ini tidak hanya mempengaruhi otot leher saya, tapi juga otot muka saya. Akibatnya, muka saya acap kali terlihat melotot dan seperti orang yang ngajak ribut, padahal itu bukan karena saya memang sedang ingin mengajak ribut, tapi itu merupakan bagian dari penyakit ini. Mungkin juga muka saya memang sudah dari sananya seperti orang yang ngajak ribut, dan diperparah dengan penyakit ini. Saya tidak tahu. Yang jelas muka yang ngajak ribut ini memiliki dampak yang serius terhadap kehidupan dan kewarasan saya.
Sejak menderita penyakit ini lima tahun yang lalu, menjadi bahan perhatian orang banyak saat berada di tempat umum sudah menjadi hal yang biasa bagi saya. Awalnya hal itu tentu membuat saya sangat tertekan, tetapi setelah sekian lama, ternyata saya masih saja tertekan. Uniknya, setelah lima tahun menjalani terapi yang rutin dan bertele-tele, penyakit saya mulai membaik, tapi sayangnya, walau gerakan kurang ajar dari leher saya sudah mulai berkurang, muka saya masih saja seperti orang ngajak ribut. Akibatnya, jika awalnya orang yang melihat saya mungkin akan berpikir, "Nih orang kok mukanya ngajak ribut yah, tapi lehernya juga gerak-gerak melulu, oh berarti nih orang lagi sakit atau ini orang memang dasarnya aneh atau ini orang gila." Tapi sekarang, setelah muka ngajak ribut saya tidak disertai dengan gerakan-gerakan leher yang aneh, orang yang melihatnya akan berpikir, "Nih orang kok mukanya ngajak ribut yah, berarti nih orang emang mau ngajak ribut nih, sikaaattt!!!"
Cibiran dari orang-orang di tempat umum yang awalnya adalah, "Aneh nih orang," atau "Stres nih orang," atau "Gila nih orang," lama-kelamaan berubah menjadi makian seperti "Apa lu!" Kadang makian yang keluar cukup kasar sehingga tidak bisa saya tulis di sini. Namun makian yang paling membekas adalah, "Dasar Cina lu!"
Karena saya tinggal di Indonesia, maka yang paling banyak melontarkan makian-makian itu adalah orang Pribumi. Mungkin kalau saya tinggal di Canada, yang memaki saya adalah orang Bule. Bahkan mungkin kalau saya tinggal di Singapore, yang memaki saya adalah sesama orang Cina. Tapi kenyataannya saya tinggal di Indonesia, dan setelah mengalami kejadian tersebut berulang-ulang dalam jangka waktu lama, hal itu tidak bisa tidak membekas di hati saya.
Beberapa bulan terakhir, saya menjadi paranoid dengan orang Pribumi. Bila melihat orang yang warna kulitnya hitam sedikit saja, bahkan dari jauh sekalipun, saya akan gemetaran, keringat dingin, kadang bahkan seperti mau pingsan. Rasa takut yang saya alami sangat hebat. Bahkan saat liburan ke Bali sekalipun, rasanya seperti masuk ke kandang singa. Pergi ke tempat umum yang awalnya masih bisa saya nikmati, sekarang menjadi sebuah mimpi buruk. Lama-kelamaan paranoid saya semakin bertambah parah. Saya bahkan menjadi takut terhadap sopir ataupun teman-teman Pribumi yang sudah lama saya kenal. Saya tidak berani keluar rumah walau hanya selangkah. Saya bahkan menjadi jarang ke gereja. Bila harus keluar rumah untuk membeli barang yang benar-benar saya butuhkan, saya harus ditemani oleh teman saya. Bahkan untuk sekedar mencukur rambut di salon langganan, saya harus ditemani oleh ibu saya.
Paranoid ini terus bertambah parah sampai akhirnya, bahkan saat saya sedang berada di dalam rumah sekalipun, saya merasa kalau orang-orang Pribumi yang lewat di depan rumah dan juga para tetangga ikut mengatai-ngatai saya, tanda patognomonik kalau paranoid ini sudah mulai memasuki tahap psikotik. Menyadari bahwa kondisi saya tidak kunjung membaik dan malah bertambah parah, saya akhirnya berkunjung ke psikiater dan seperti sudah saya duga, psikiater meresepkan saya obat anti psikotik. Berkunjung ke psikiater dan minum obat anti psikotik rasanya sudah cukup untuk menggambarkan tingkat keseriusan dari masalah yang saya hadapi. Tidak ada orang waras yang bersedia untuk minum obat dari psikiater kalau masalahnya masih bisa ia hadapi sendiri.
Yang membuat saya kecewa, sang psikiater tampaknya benar-benar hanya mengandalkan obat tersebut untuk menyelesaikan semua permasalahan saya. Saya berharap sang psikiater akan memberikan Cognitive Behaviour Therapy, konseling, ataupun tips dan trik untuk saya mengatasi ketakutan ini. Gambaran yang ada di benak saya adalah saya berbaring di kursi panjang dan menceritakan semua keluh-kesah saya, sementara sang psikiater mendengarkan dan membuat catatan, seperti yang ditampilkan di film-film. Tapi ternyata tidak. Kenyataannya, kunjungan ke psikiater ini sama seperti ketika saya berobat ke dokter kulit untuk mengobati jerawat ataupun ke dokter umum untuk mengobati batuk pilek. Saya duduk, menceritakan gejala yang saya rasakan, dokter meresepkan obat, menyerahkan resep itu ke saya, dan saya pulang, dengan resep di tangan sebagai kunci jawaban untuk mengatasi semua gejala yang saya rasakan. Sang dokter tidak akan bertanya, "Apa perasaan anda terhadap gejala yang muncul di anda?" atau "Menurut anda, kenapa gejala itu bisa muncul?" atau "Menurut anda, bagaimana cara untuk mengatasi akar penyebab timbulnya gejala itu?"
Pada awalnya, obat ini memang sangat membantu saya. Gejala psikotik dan pikiran irasional mulai lenyap. Saya tidak lagi merasa orang yang lewat di depan rumah ataupun para tetangga mengatai saya tanpa alasan apapun. Akan tetapi saya tetap takut pada orang Pribumi. Bila bertemu mereka, saya merasa takut dan tidak nyaman. Seolah bagi saya, mereka adalah momok yang membenci kehadiran saya dan akan mengatai atau menyakiti saya. Saya sudah minum obat anti psikotik selama beberapa minggu, dan saya tidak merasa lagi ada kemajuan yang bisa diberikan obat ini. Saya tidak merasa kalau obat ini adalah jawaban untuk menghilangkan ketakutan saya. Di samping itu, tidak seperti obat jerawat ataupun obat flu, efek samping obat ini sangat berat dan malahan mengganggu produktivitas saya sehari-hari. Akhirnya saya putuskan untuk stop mengonsumsi obat ini dan juga tidak meneruskan kunjungan saya ke sang psikiater.
Lepas dari psikiater, saya mulai berkontemplasi untuk mencari jawaban atas permasalahan ini. Saya mulai merenung, kenapa saya harus takut dengan orang Pribumi? Kenapa saya harus memandang mereka sebagai momok yang begitu mengerikan? Saya kenal dengan banyak orang Pribumi dan mereka semua baik dan sopan terhadap saya, rasanya tidak adil kalau hanya karena perlakuan segelintir beberapa orang Pribumi terhadap saya, lantas saya memberikan stereotip dan prasangka buruk terhadap mereka semua. Tapi, seberapapun kerasnya logika dan hati nurani saya mencoba meyakinkan, kenyataannya saya tetap saja takut terhadap orang Pribumi. Saya bahkan acap kali bersembunyi bila ada tukang air, tukang listrik, ataupun petugas dari langganan internet yang datang ke rumah. Pernah suatu kali AC kamar saya rusak dan harus direparasi. Beberapa hari sebelum kedatangan sang tukang reparasi AC, saya tidak bisa tidur. Dan saat hari H tiba, hanya untuk menemani sang tukang reparasi AC yang sebenarnya juga adalah orang yang ramah, tingkat ketegangan yang saya rasakan seperti sedang terjun ke medan perang.
Saya amat terganggu dengan ketakutan ini, saya merasa kalau ketakutan ini tidak bisa saya atasi, hidup saya akan menjadi tidak maksimal dan tidak produktif. Saya melanjutkan perenungan saya, dan pada akhirnya, jawaban dari ketakutan saya hanya satu. Jawabannya sebenarnya amat sederhana, dan jawaban tersebut sama seperti judul artikel ini. Saya adalah seorang rasis. Ya, saya seorang rasis. Sekali lagi saya ucapkan supaya jadi pas tiga kali, saya adalah seorang rasis.
Setelah mengingat-ingat lagi dan melewati beberapa fase penyangkalan, saya akui bahwa sudah lama bibit-bibit rasisme ada dalam diri saya. Saya mungkin sebelumnya memiliki banyak teman Pribumi, tapi tetap saja saya selalu menjaga jarak dengan mereka. Tingkat persahabatan saya tidak akan sedalam dan seakrab dengan sesama orang Cina.
Agak susah untuk mengetahui kapan persisnya benih rasisme timbul dalam hati saya. Mungkin rasisme itu tertanam secara perlahan secara tidak sengaja oleh orang tua saya. Orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya untuk membenci Pribumi, tapi mereka selalu mengingatkan saya untuk berhati-hati dengan orang Pribumi. Untuk memberikan orang tua saya sedikit pembelaan, mereka lahir pada tahun 60'-an. Mereka menghabiskan masa muda mereka pada masa Orde Baru. Di masa itu, kehidupan orang Cina tidaklah semudah pada masa sekarang, terutama setelah era Gus Dur. Orang Cina akan dipersulit bila harus mengurus surat-surat resmi ataupun izin usaha. Itulah kenapa banyak orang Cina yang mengganti nama mereka di akta lahir ataupun KTP menjadi lebih "ke-Pribumi-an", supaya ke-Cina-an mereka tidak terlalu kentara. Orang tua saya juga seringkali mengingatkan saya supaya jangan sampai berurusan dengan polisi ataupun aparat negara lainnya. Karena polisi akan lebih membela hak dan kepentingan orang Pribumi dibanding orang Cina, bahkan ketika orang Cina-lah yang menjadi korban dalam suatu perkara.
Dahulu saya selalu menganggap orang tua saya konyol, kalau ketakutan mereka itu berlebihan, dan kita juga sekarang telah hidup di era Milenium. Prasangka dan stereotip seperti itu sudah ketinggalan zaman. Tapi mungkin, seperti yang Sigmund Freud ajarkan, hal-hal negatif yang diceritakan orang tua saya itu tertanam kuat dalam alam bawah sadar atau Id saya, tanpa saya sadari. Selama ini saya berhasil mengontrol Ego atau alam sadar saya untuk mengingatkan bahwa beranggapan bahwa Pribumi itu jahat adalah hal yang tidak baik. Tapi setelah depresi yang berkepanjangan dan juga kejadian traumatis akhir-akhir ini, pertahanan Ego saya runtuh dan Id saya, yang penuh dengan insting primitif seperti ketakutan dan agresi, mengambil alih.
Pada akhirnya, saya menyadari bahwa untuk menghilangkan ketakutan ini, saya harus mengakui terlebih dahulu bahwa memang saya dasarnya adalah seorang rasis. Rasisme itulah yang membangun dinding pemisah antara saya, orang Cina, dengan orang Pribumi. Saat konsultasi dengan psikiater ataupun teman saya, saya acap kali membela diri dan mengatakan kalau saya tidak rasis, karena rasis itu membenci Pribumi, sementara saya takut dengan Pribumi. Tapi takut dan benci bagaikan dua sisi pada satu koin yang sama. Saya tidak ada bedanya dengan orang-orang yang menerima bahwa diri mereka memang rasis dan membenci golongan atau ras yang berbeda dengan mereka. Tidak ada orang yang senang membenci. Membenci itu melelahkan. Kebencian mereka juga berasal dari ketakutan, takut pada hal yang tidak mereka pahami. Ketakutan yang sama seperti saya.
Tujuan saya membuat tulisan ini, selain untuk terapi, adalah untuk membuat semacam pernyataan bahwa saya adalah seorang rasis, dan saya malu akan hal itu. Alam super-ego saya mengingatkan bahwa sifat rasisme saya ini adalah salah dan harus diperbaiki. Sifat ini hanya akan membawa kerugian dan malapetaka untuk saya sendiri. Orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan ataupun kebencian adalah orang yang membiarkan insting primitifnya mengontrol dirinya, dan akhirnya hidupnya akan semakin jauh dari ideal self-nya dan tidak akan mencapai potensi maksimal.
Saya memutuskan untuk berhenti menyalahkan paradigma Orde Baru yang sebenarnya juga bukan mengajarkan untuk membenci orang Cina, tapi untuk membenci ideologi komunisme. Sayangnya memang negara RRC saat itu merupakan salah satu kiblat komunisme terbesar di dunia, sehingga mungkin sampai sekarang orang Pribumi sudah terlanjur untuk mengasosiasikan orang Cina dengan komunisme dan segala mudarat yang disebabkan paham itu. Saya juga memutuskan untuk berhenti menyalahkan segelintir orang Pribumi yang mungkin pernah mengatai saya. Saya bahkan memutuskan untuk berhenti menyalahkan penyakit Dystonia saya. Hanya rasisme yang ada di hati saya sendiri inilah yang perlu dibenci dan diperbaiki.
Bila kebetulan anda yang membaca tulisan saya ini adalah seorang Pribumi, saya minta maaf kalau tulisan ini menyinggung perasaan anda, hal itu sama sekali bukan maksud saya. Tulisan ini saya maksudkan sebagai permintaan maaf atas kerasisan saya, dan lebih dari itu, juga merupakan permintaan tolong. Bila anda seorang Pribumi, saya harap anda tetap sudi untuk berteman dengan saya. Tolonglah ubah prasangka negatif saya ini dan bantulah saya untuk keluar dari belenggu paranoid, ketakutan, dan rasisme ini. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan rasisme, hanya kehangatan, keterbukaan hati, dan toleransi terhadap perbedaanlah yang dapat melakukannya.
Saya selalu bermimpi untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, tapi bagaimana mungkin hal itu bisa saya lakukan kalau saya bahkan tidak bisa berdamai dengan tetangga saya sendiri. Seperti yang Michael Jackson pernah ucapkan, jika anda ingin menciptakan dunia yang lebih baik, mulailah dari sosok yang ada di dalam cermin.

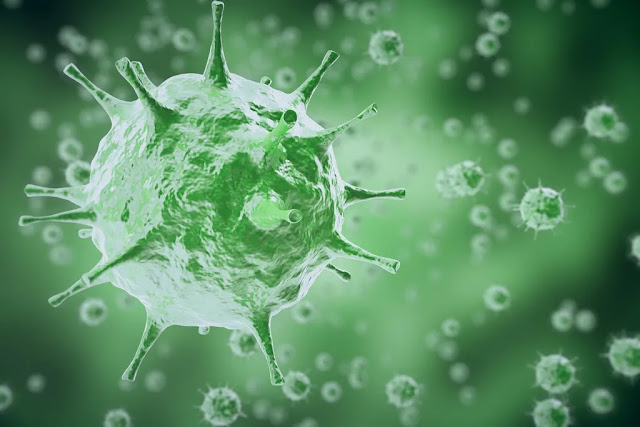

Comments
Post a Comment